 (MI/Seno)
(MI/Seno)
MENTERI Kesehatan memiliki ambisi besar untuk mereformasi sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia. Salah satu gagasan utamanya ialah meluncurkan program hospital base, sebuah skema Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang memberikan kewenangan kepada rumah sakit untuk secara langsung menyelenggarakan pendidikan dan meluluskan dokter spesialis.
Selama ini, peran tersebut dijalankan oleh universitas dengan rumah sakit sebagai wahana pendidikan klinik. Dalam konsep hospital base, rumah sakit tidak lagi sekadar menjadi tempat praktik atau wahana pendidikan, tetapi naik kelas menjadi penyelenggara utama pendidikan spesialis. Kurikulum, proses pembelajaran, hingga kelulusan berada di bawah kendali rumah sakit.
Sejatinya, program ini bukanlah ide baru. Beberapa negara memang menerapkan skema hospital base, tetapi selalu dengan prasyarat sistem kesehatan yang matang, tata kelola rumah sakit yang kuat, serta mekanisme kontrol kualitas yang ketat. Masalahnya, konteks Indonesia sangat berbeda. Sejak awal, para ahli pendidikan kedokteran, kolegium, akademisi, dan organisasi profesi telah mengingatkan bahwa program hospital base tidak tepat diterapkan di Indonesia. Terlalu banyak isu mendasar dan kendala struktural yang belum terselesaikan. Peringatan ini bukanlah penolakan tanpa dasar, melainkan hasil pembacaan realistis terhadap kapasitas sistem kesehatan nasional.
Lebih dari tiga tahun sejak isu hospital base pertama kali diangkat, program ini belum juga berjalan sesuai yang diharapkan. Tidak ada lonjakan produksi dokter spesialis sebagaimana dijanjikan. Padahal, ketika gagasan ini pertama kali dilempar ke publik, Menteri Kesehatan menyampaikannya dengan penuh euforia. Program ini diklaim mampu memproduksi ribuan dokter spesialis dalam waktu singkat dan menjadi solusi atas kekurangan dokter spesialis di Indonesia. Kenyataan memang tidak seindah retorika. Program ini tersendat, menghadapi resistensi, dan menemui banyak hambatan teknis maupun konseptual.
Meski demikian, alih-alih melakukan evaluasi mendalam atau mundur dari gagasan yang terbukti bermasalah, Menteri Kesehatan justru terus mencari celah agar program ini tetap bisa dijalankan. Salah satu strategi yang kini dijalankan ialah menggandeng universitas. Strategi ini menjadi sangat ironis. Karena, pada tahap awal, hospital base digadang-gadang sebagai sistem independen, tanpa ketergantungan pada universitas. Rumah sakit disebut mampu berdiri sendiri sebagai institusi pendidikan spesialis.
Kini, Menteri Kesehatan mulai menyadari bahwa harapan tersebut tidak realistis. Tanpa dukungan universitas, program ini nyaris mustahil berjalan. Maka, strategi pun diubah. Menteri Kesehatan berusaha menggandeng dan membujuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk mewujudkan ambisi hospital base ini. Istilahnya diperhalus menjadi ‘program kolaborasi’.
Gayung bersambut. Kemendiktisaintek menyatakan kesiapan untuk mem-back up program ini dengan meminta sejumlah universitas mendukung pembukaan PPDS di berbagai rumah sakit. Target yang dicanangkan pun sangat ambisius: 155 program studi pada tahun 2026 dan meningkat menjadi 400 program studi pada 2030. Rumah sakit yang akan dilibatkan sebanyak 120 pada 2026 dan meningkat menjadi 400 pada 2030.
Angka ini mencengangkan. Bahkan jika sistem berjalan normal, target tersebut tetap terasa tidak masuk akal. Membuka ratusan program pendidikan spesialis bukan sekadar soal administrasi. Ia menyangkut ketersediaan staf pengajar, kualitas rumah sakit pendidikan, kesiapan sarana prasarana, sistem evaluasi, hingga jaminan keselamatan pasien.
Meski Kementerian Kesehatan dan Kemendiktisaintek berulang kali menyatakan bahwa standar kualitas akan tetap dijaga, rencana yang begitu masif justru menunjukkan kecenderungan sebaliknya. Produksi dalam jumlah besar hampir selalu berbanding terbalik dengan kualitas, terlebih dalam pendidikan kedokteran yang bersifat kompleks dan berisiko tinggi. Jika target kuantitatif menjadi prioritas utama, pelonggaran standar dan pemudahan proses PPDS menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Bahkan, Kemendiktisaintek sendiri secara terbuka menyebut skema ini sebagai ‘program dipercepat’.
Pertanyaannya, apakah program dokter spesialis mesti dipercepat demi angka-angka statistik? Program PPDS itu memiliki standar; peserta harus telah melihat sekian pasien, melakukan tindakan sendiri terhadap sekian pasien, merawat sekian pasien. Itu standar yang selalu disesuaikan dengan standar internasional.
Di luar negeri, tidak ada institusi yang mempercepat produksi dokter spesialis dengan alasan pemenuhan data statistik. Rencana Indonesia benar-benar anomali.
ISU TIDAK RELEVAN
Saat ini, jumlah dokter spesialis di Indonesia berkisar 52 ribu orang. Angka ini dihasilkan oleh puluhan universitas yang menyelenggarakan PPDS dengan standar yang diakui secara nasional maupun internasional. Para lulusan tidak hanya mengabdi di dalam negeri, tetapi juga bekerja dan diakui kompetensinya di luar negeri. Sistem ini berjalan relatif stabil, konsisten, dan berada dalam koridor akademik yang jelas. Lantas, mengapa tiba-tiba Menteri Kesehatan berambisi besar mengubah sistem ini secara radikal?
Narasi yang diangkat terdengar heroik: Indonesia mengalami krisis dokter spesialis. Rasio dokter spesialis, katanya, tidak memenuhi standar WHO. Target ideal, katanya, ialah 0,28 dokter spesialis per 1.000 penduduk. Dalam konteks ini, Indonesia dianggap masih kekurangan sekitar 29.000–30.000 dokter spesialis. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, jumlah dokter spesialis harus dipacu. Jalan keluarnya, menurut narasi Menkes, ialah hospital base.
Sayangnya, narasi ini bermasalah sejak dari hulu. Pertama, WHO tidak pernah menetapkan standar rasio dokter spesialis terhadap jumlah penduduk. Yang ada ialah indikator umum jumlah dokter (general physician) per populasi. Itu pun bersifat rekomendatif dan kontekstual. Rasio yang dikemukakan oleh pemerintah hanyalah rekomendasi mereka. Menggunakan WHO sebagai legitimasi krisis dokter spesialis adalah klaim yang tidak akurat.
Kedua, isu kekurangan dokter bukanlah masalah unik Indonesia. Hampir semua negara menghadapi tantangan distribusi dan kecukupan tenaga kesehatan, termasuk negara maju. Namun, sebagian besar negara memilih memperbaiki sistem insentif, distribusi, dan tata kelola; bukan dengan mengorbankan fondasi pendidikan kedokteran.
Jika memang ada masalah, mengapa bukan optimalisasi universitas yang ada? Mengapa bukan memperkuat fakultas kedokteran, memperbaiki kapasitas rumah sakit pendidikan yang sudah berjalan, atau memperbaiki sistem penempatan dokter spesialis ke daerah? Mengapa solusi yang dipilih justru menciptakan sistem baru yang sarat risiko?
NAMA BARU, ISI LAMA
Salah satu kekeliruan terbesar dalam narasi hospital base ialah seolah-olah rumah sakit selama ini tidak berperan dalam pendidikan dokter spesialis. Faktanya, sejak awal, PPDS yang dijalankan universitas memang berbasis rumah sakit. Pendidikan spesialis tidak pernah berlangsung di ruang kelas semata. Seluruh proses klinik, tindakan, dan pembelajaran praktik dilakukan di rumah sakit.
Sebagai contoh, PPDS Universitas Indonesia menjalankan pendidikan dan pelatihan di berbagai rumah sakit seperti RSUI, RS Jantung Harapan Kita, dan RS Kanker Dharmais, juga banyak rumah sakit lainnya. Rumah sakit-rumah sakit tersebut telah lama berfungsi sebagai wahana pendidikan, lengkap dengan sistem supervisi, audit mutu, dan jejaring akademik.
Dengan kata lain, hospital base sejatinya hanyalah nama baru untuk isi lama. Yang berubah bukanlah lokasinya, melainkan struktur kewenangan. Dari sistem akademik berbasis universitas yang relatif independen, kewenangan dialihkan ke rumah sakit yang secara struktural berada di bawah birokrasi pelayanan. Perubahan ini bukan sekadar administratif, tetapi menyentuh jantung pendidikan kedokteran.
Namun, persoalan sebenarnya bukanlah jumlah absolut, melainkan kualitas pendidikan, distribusi, kapasitas pendidikan, dan prioritas sistem kesehatan nasional. Terkait dengan distribusi, sekitar 59% dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara banyak provinsi di luar Jawa masih menyisakan kekosongan spesialis tajam. Ini adalah persoalan sebenarnya.
Pendidikan dokter spesialis bukanlah proses produksi massal. Ia adalah proses pembentukan kompetensi, etika, dan profesionalisme yang membutuhkan lingkungan akademik yang kritis dan independen. Ketika pendidikan terlalu dekat dengan kepentingan pelayanan, risiko konflik kepentingan meningkat. Pasien bisa menjadi objek, peserta didik bisa menjadi tenaga murah, dan kualitas pendidikan menjadi korban. Pada titik ini, program hospital base tampak bukan sebagai solusi, melainkan sebagai eksperimen besar dengan risiko tinggi.
Ambisi yang tidak ditopang kesiapan sistem hanya akan melahirkan kegagalan. Jika dipaksakan, bukan tidak mungkin Indonesia akan membayar mahal dengan turunnya kualitas dokter spesialis, rusaknya ...

 2 hours ago
3
2 hours ago
3





















:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5274842/original/066514900_1751813073-Thibaut_Courtois.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5425070/original/013103300_1764211382-ARNE.jpg)





:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5425161/original/045302800_1764215576-atletico_madrid_vs_inter_milan.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5079575/original/007201300_1736152577-1735888186921_ciri-tensi-rendah.jpg)

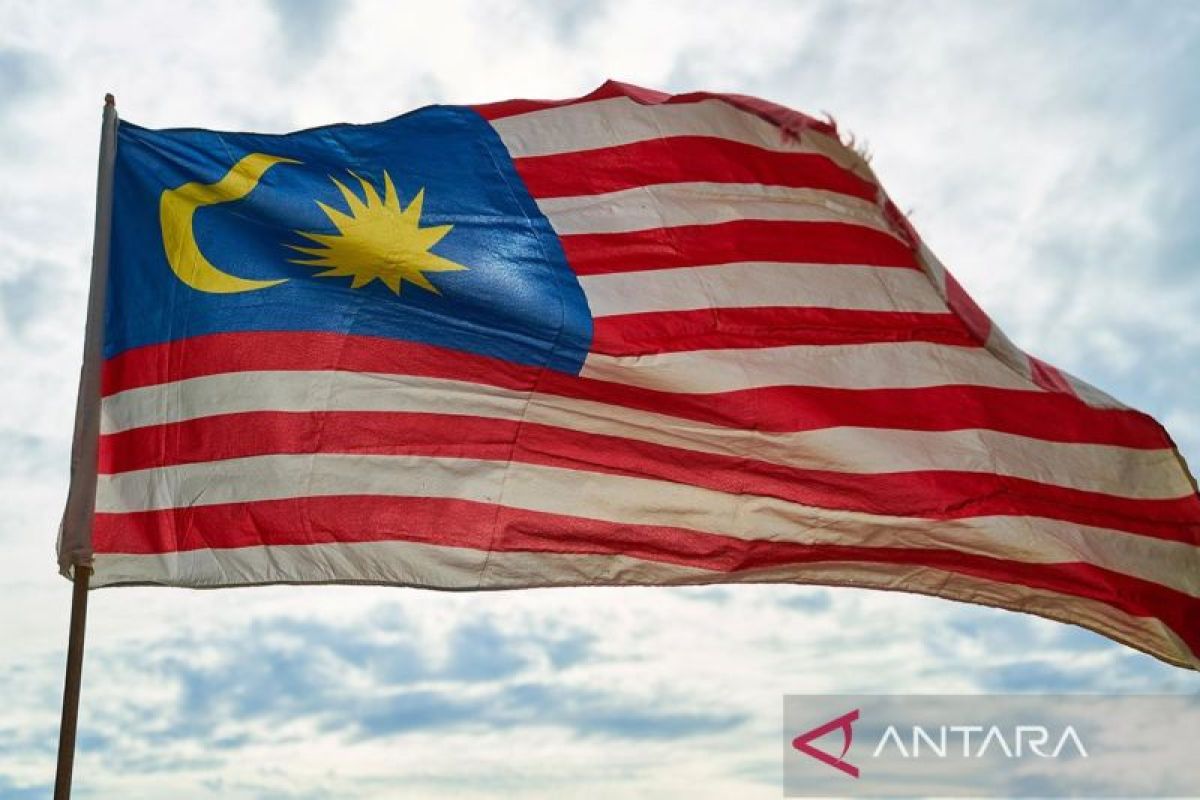
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4668817/original/047647600_1701319471-person-holding-world-aids-day-ribbon.jpg)


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5424978/original/015359200_1764192932-virgil_van_dijk_protes_liverpool_psv_ap_jon_super.jpg)



 English (US) ·
English (US) ·