 (Dok. Pribadi)
(Dok. Pribadi)
BENCANA memang sering hadir tanpa memberikan ruang memilih, tetapi cara manusia meresponsnya selalu lahir dari pilihan moral dan politik. Banjir lumpur di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November 2025 tidak hanya menyisakan luka ekologis dan kemanusiaan, tetapi juga membuka peta privilese dan relasi kuasa yang bekerja di tengah masyarakat. Dari peristiwa itu, tampak jelas siapa yang memiliki akses dan jaringan, siapa yang memegang sumber daya, serta siapa yang berhak menentukan arah bantuan, sementara pertanyaan terpenting kerap terabaikan: untuk kepentingan siapa semua privilese tersebut digunakan. Dalam situasi darurat, privilese hadir lebih dulu sebelum kuasa dijalankan--ia menentukan siapa dapat bergerak paling cepat, membuka jalur pertolongan, dan membuat suaranya didengar--tetapi privilese baru benar-benar menjelma kuasa ketika seseorang memilih menggunakannya untuk bertindak, bukan untuk berdiam.
Kuasa tidak selalu hadir sebagai kebijakan negara, tetapi juga melalui keputusan kecil yang berdampak nyata: memilih diam atau bertindak, menjaga jarak atau mendekat, mengejar citra atau menolong dengan tulus. Karena itu, kuasa bukan hanya soal kemampuan untuk bertindak, melainkan juga soal orientasi moral dalam menggunakan privilese yang dimiliki.
Di tengah wajah ganda penggunaan kuasa itulah kita memerlukan ruang belajar sosial yang konkret. Pendidikan seharusnya tidak hanya mengajarkan definisi empati, tetapi juga melatih keberanian etis untuk bertindak ketika krisis hadir.
MEMAHAMI PRIVILESE DAN KUASA
Privilese dapat dipahami sebagai posisi sosial individu atau kelompok, yang karena identitasnya, mendapat keuntungan berupa akses yang lebih besar kepada sumber daya, jaringan, dan legitimasi (Sensoy & DiAngelo, 2017). Memiliki privilese tidak secara otomatis bermasalah. Ia menjadi persoalan ketika kita bertanya bagaimana privilese itu digunakan. Apakah ia dipakai untuk memperkuat kepentingan diri dan kelompok sendiri atau digunakan untuk kepentingan bersama dan keadilan sosial.
Selanjutnya, privilese memiliki relasi dengan kuasa, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan dan memengaruhi keadaan. Kita kerap memahami kuasa sebagai sesuatu yang melekat pada pemerintah atau elite. Padahal, kuasa selalu ada secara relasional antara siapa pun dalam kehidupan sehari-hari (Foucault, 1980). Kuasa dimiliki bukan hanya oleh negara, melainkan juga oleh aktor lain seperti individu, organisasi masyarakat, dan institusi, termasuk sekolah. Mereka memiliki akses dan pengaruh yang kemudian dihadapkan pada pilihan bagaimana akan menggunakan kuasa tersebut dan untuk kepentingan siapa.
Bencana banjir lumpur di tiga provinsi di Pulau Sumatra memperlihatkan dengan jelas dua wajah penggunaan kuasa. Di satu sisi, kita menyaksikan penggunaan kuasa yang terwujud dalam respons lamban dan tidak menyeluruh. Kuasa juga kadang tampil dalam bentuk simbolisme seperti foto dan spanduk, tetapi kebutuhan dasar korban bencana tidak benar-benar dipenuhi. Dalam situasi seperti ini, kuasa tampak memperlebar jarak antara yang selamat dan yang terdampak. Di sisi lain, ada praktik sadar oleh para pihak yang memiliki privilese dan kuasa, baik individu maupun kelompok, untuk secara cepat membantu para korban seperti dengan mengirimkan logistik kebutuhan hidup sehari-hari dan menyediakan layanan kesehatan.
MENGAJARKAN PRIVILESE DAN KUASA UNTUK KEBAIKAN
Praktik penggunaan privilese dan kuasa secara etis terlihat pada Sekolah Sukma Bangsa yang berada di Pidie, Bireuen, dan Lhokseumawe. Sekolah ini lahir pada 2006 sebagai respons atas gempa dan tsunami Aceh 2004 sehingga sejak awal menempatkan nilai kemanusiaan sebagai fondasi utama geraknya. Pengalaman historis tersebut membentuk kesadaran bahwa pendidikan tidak hanya soal ruang kelas, tetapi juga keberpihakan pada martabat manusia ketika krisis terjadi.
Saat banjir lumpur melanda Aceh pada November 2025, warga belajar Sekolah Sukma Bangsa menyadari privilese yang mereka miliki berupa jaringan, akses, dan kapasitas organisasi. Kesadaran itu berubah menjadi pilihan moral untuk tidak berdiri sebagai penonton. Guru, siswa, dan tenaga pendukung bergerak bersama menggalang donasi, menyalurkan kebutuhan dasar, membersihkan rumah warga, membuka dapur umum, serta mendistribusikan makanan siap saji ke lokasi terdampak.
Mereka juga memahami bahwa bencana melukai aspek psikis, terutama anak-anak. Karena itu, diselenggarakan pendampingan psikososial bagi anak korban banjir yang dilaksanakan di lingkungan sekolah. Kegiatan ini berjalan selama dua minggu di masa libur ketika sebagian besar sekolah berhenti beraktivitas. Komitmen tersebut dilakukan secara sukarela tanpa imbalan apa pun sebagai bentuk tanggung jawab etis atas privilese yang dimiliki.
Inisiatif warga dan sekolah tidak dapat menggantikan tanggung jawab negara, tetapi menjadi pengingat bahwa privilese masyarakat sipil seharusnya melengkapi, bukan menambal kekosongan kebijakan. Upaya tersebut memiliki keterbatasan jangkauan, koordinasi, dan ketergantungan pada relawan sehingga perannya lebih sebagai dorongan moral agar kebijakan publik hadir secara lebih terencana, adil, dan berpihak pada korban.
REFLEKSI PRIVILESE DAN KUASA
Dilihat dari sudut pandang perdamaian, usaha yang dilakukan oleh Sekolah Sukma Bangsa dapat disebut sebagai kontribusi menuju perdamaian positif (Galtung, 1969) yang tidak hanya mewujudkan ketiadaan kekerasan langsung, tetapi juga ikut menghadirkan keadilan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar, khususnya hak anak untuk mendapatkan pendidikan, rasa aman, dan dukungan psikososial.
Melalui kegiatan respons terhadap bencana yang dilaksanakan oleh Sekolah Sukma Bangsa, warga belajar tidak hanya mendengar ceramah tentang empati dan solidaritas. Para guru dan tenaga pendukung menunjukkan bahwa memiliki privilese berupa akses dan sumber daya memberikan mereka tanggung jawab moral yang lebih besar. Sementara itu, siswa yang terlibat dalam kegiatan tersebut belajar bahwa privilese tidak untuk dinikmati sendiri, tetapi jug harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara etis.
Kegiatan membantu korban bencana digunakan untuk mendidik generasi muda tentang bagaimana menggunakan privilese dan kuasa secara bermoral. Ini ialah pembelajaran jangka panjang. Kelak, ketika para siswa tumbuh dewasa mereka telah menyadari bahwa privilese dan kuasa yang mereka miliki memberikan pilihan, pilihan yang mereka ambil harus selalu berpihak pada kemanusiaan dan keadilan sosial.

 2 hours ago
3
2 hours ago
3





















:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5274842/original/066514900_1751813073-Thibaut_Courtois.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5425070/original/013103300_1764211382-ARNE.jpg)





:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5425161/original/045302800_1764215576-atletico_madrid_vs_inter_milan.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5079575/original/007201300_1736152577-1735888186921_ciri-tensi-rendah.jpg)

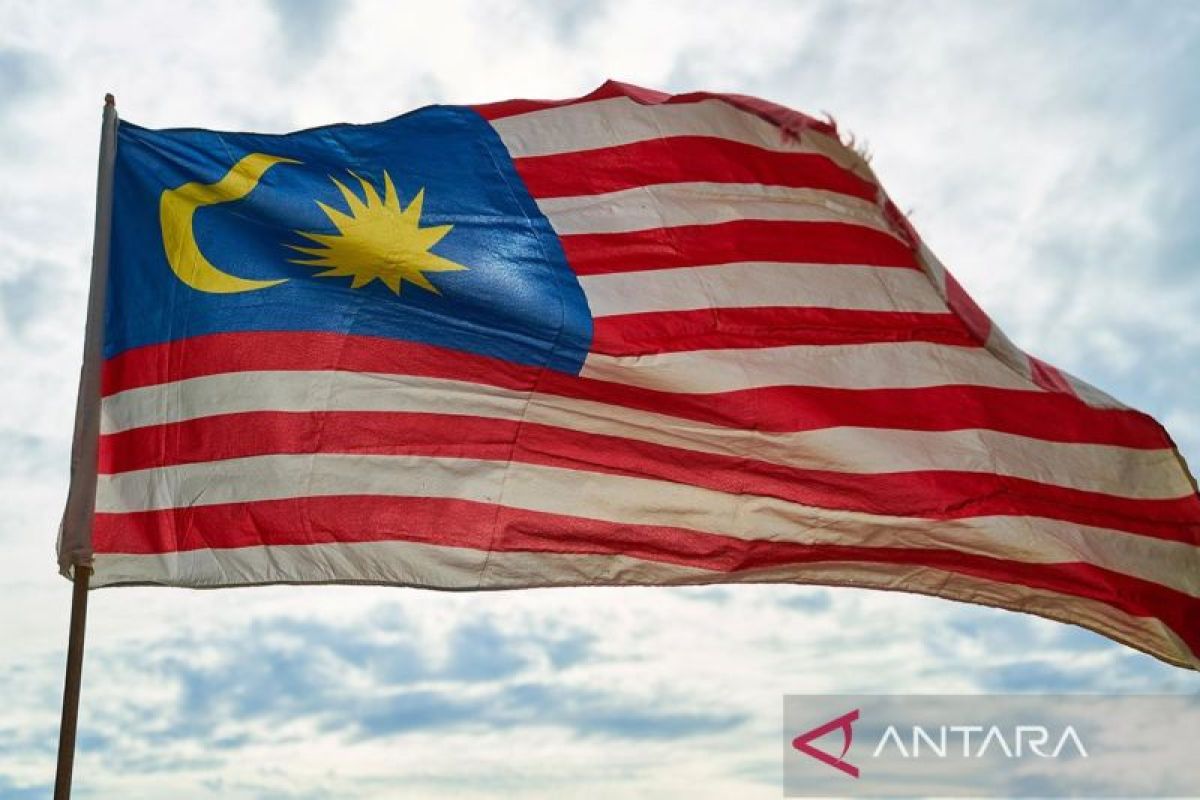
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4668817/original/047647600_1701319471-person-holding-world-aids-day-ribbon.jpg)


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5424978/original/015359200_1764192932-virgil_van_dijk_protes_liverpool_psv_ap_jon_super.jpg)



 English (US) ·
English (US) ·