Dalam banyak diskursus agama, etika, dan psikologi populer, compassion (welas asih) kerap dipahami sebagai tindakan moral: sesuatu yang baik, luhur, dan seharusnya dilakukan. Kita diajarkan untuk bersikap penuh kasih, berempati, dan membantu sesama, seolah compassion adalah sebuah keputusan rasional yang bisa diambil kapan saja, tanpa keterkaitan dengan kondisi batin dan tubuh kita.
Pemahaman ini tampak masuk akal. Berbagai penelitian dalam psikologi positif mendukung gagasan bahwa altruisme dan perilaku menolong berkaitan dengan kebahagiaan dan kesehatan. Orang yang meluangkan waktu, tenaga, atau sumber daya untuk membantu orang lain cenderung melaporkan tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Beberapa studi longitudinal bahkan menunjukkan bahwa keterlibatan dalam aktivitas relawan berkorelasi dengan penurunan risiko kematian, terutama ketika motivasinya benar-benar altruistik—yakni ingin membantu orang lain, bukan sekadar mencari manfaat pribadi.
Singkatnya, menolong orang lain memang baik, bukan hanya secara moral, tetapi juga secara psikologis dan biologis.
Namun, di titik inilah muncul sebuah ironi.
Di balik semua narasi indah tentang compassion, kita sering menjumpai paradoks yang mengganggu:
Fenomena ini muncul pada aktivis sosial, pekerja kemanusiaan, guru, tenaga kesehatan, pemuka agama, terapis, relawan, bahkan orang tua yang berjuang keras demi keluarganya.
Secara publik mereka terlihat heroik, tetapi secara personal mereka rapuh. Ada kelelahan kronis, kepahitan, bahkan kemarahan tersembunyi yang tidak sejalan dengan citra moral yang mereka pegang.
Fenomena ini mengajak kita untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar:
Apakah compassion benar-benar berawal dari moralitas?
Ataukah compassion justru harus berakar pada kondisi tubuh (bodily state) yang teregulasi, sebelum berkembang menjadi nilai, niat, dan tindakan?
Seyogyanya, compassion terlebih dahulu harus mampu menjalankan fungsinya dalam meregulasi tubuh. Barulah kemudian ia dapat berkembang menjadi tindakan moral yang sehat dan berkelanjutan.
Compassion seharusnya berakar pada fisiologi sebelum berkembang menjadi aturan etika.
Sebelum menjadi nilai, niat, dan tindakan, compassion perlu bermula sebagai kondisi sistem saraf yang teregulasi di dalam tubuh.
Ketika compassion terintegrasi di tingkat tubuh, tubuh akan:
Dalam kondisi ini, compassion muncul secara alami. Ia tidak dipaksakan. Tubuh pun cukup teregulasi untuk menghadirkan keterbukaan.
Compassion yang bersifat moralitas semata tanpa melibatkan regulasi tubuh akan berubah menjadi kewajiban.

 2 days ago
1
2 days ago
1





















:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5274842/original/066514900_1751813073-Thibaut_Courtois.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5425070/original/013103300_1764211382-ARNE.jpg)





:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5425161/original/045302800_1764215576-atletico_madrid_vs_inter_milan.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5079575/original/007201300_1736152577-1735888186921_ciri-tensi-rendah.jpg)

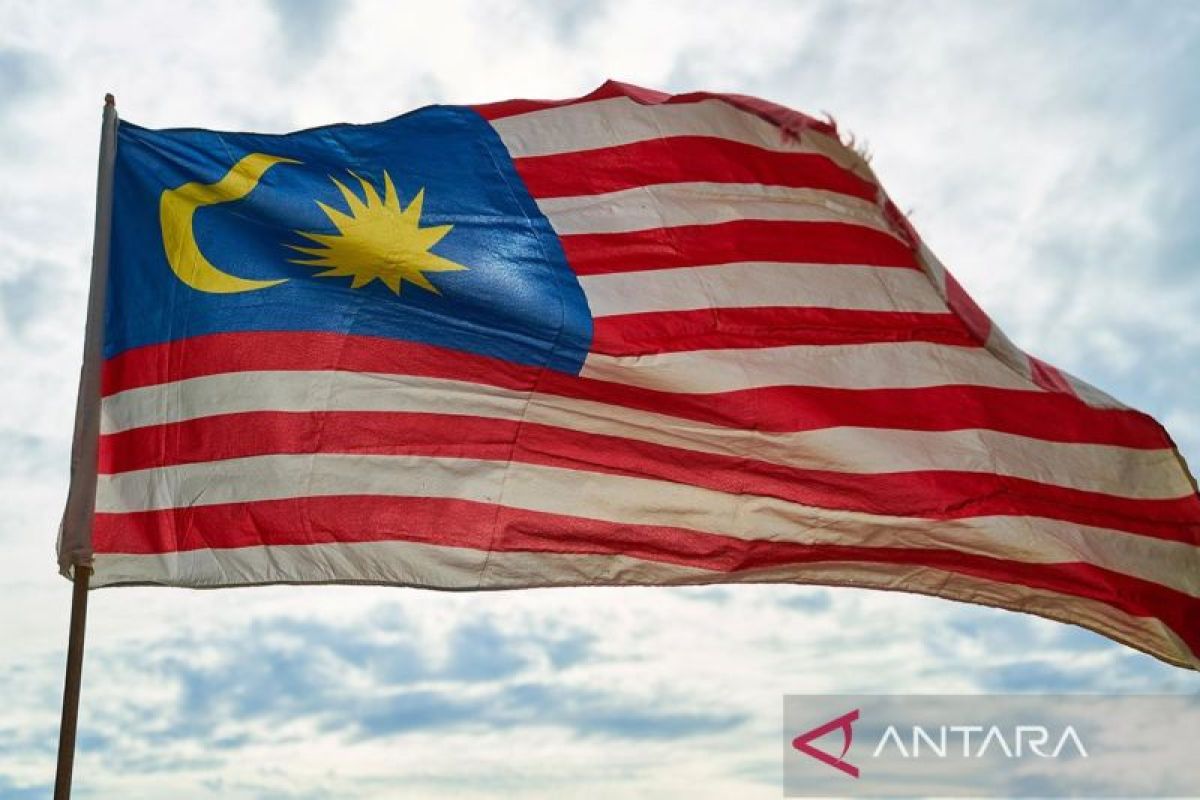
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4668817/original/047647600_1701319471-person-holding-world-aids-day-ribbon.jpg)


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5424978/original/015359200_1764192932-virgil_van_dijk_protes_liverpool_psv_ap_jon_super.jpg)



 English (US) ·
English (US) ·